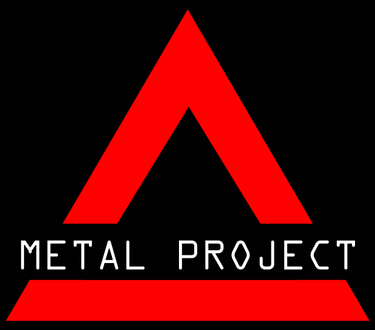Skena Musik Metal di Indonesia: Lebih dari Sekadar Gerombolan
Skena musik METAL di Indonesia bukan cuma sekedar gerombolan orang yang mencintai musik yang identik dengan distorsi gitar agresif, tempo cepat, hingga suara vokal yang "berat".
ARTICLE
AMPS RECORDS
10/14/20255 min read


Skena musik METAL di Indonesia bukan cuma sekedar gerombolan orang yang mencintai musik yang identik dengan distorsi gitar agresif, tempo cepat, hingga suara vokal yang "berat".
Musik Metal di Tanah Air menjelma jadi gerakan, identitas, dan kadang bentuk perlawanan musisi lokal terhadap skena arus utama. Dari era awal 90-an hingga masuknya gelombang metalcore, hardcore dan extreme metal modern, band-band metal lokal telah menunjukkan daya tahan luar biasa.
Bahkan, mengutip RRI, Indonesia merupakan negara dengan skena musik metal terbesar Asia. Band metal aktif Tanah Air disebut-sebut mencapai 2.113 band per Maret 2025.
Namun di balik semangat itu, ada tantangan besar yang masih membayangi, terutama di era digital sekarang. Penulis mencoba menelaah tantangan-tantangan bagi band-band lokal, khususnya yang bergerak di skena musik METAL.
1. Biaya Produksi dan Distribusi
Mayoritas band metal di Indonesia, yang identik dengan skena musik underground, mayoritas masih beroperasi secara independen alias mengurus segalanya secara mandiri atau DIY (Do It Yourself). Mulai dari rekaman, mixing, mastering, hingga distribusi digital, hampir semuanya dilakukan dengan dana pribadi.
Meski teknologi sudah memudahkan, tantangan tetap ada, studio berkualitas masih mahal, peralatan sering terbatas, dan standar produksi global kian tinggi. Akibatnya, banyak rilisan metal lokal yang secara musikal berkualitas, kurang terdengar “matang” di level teknis.
Padahal kualitas akhir dari produksi bisa jadi pembeda besar di platform seperti Spotify atau YouTube.
Komposisi musik maupun lirik yang menggugah, tapi tanpa dukungan produksi rekaman mumpuni, bakal menghambat sebuah band untuk menghasilkan karya dengan kualitas sound yang baik, terutama di platform digital.
Belum lagi jika berbicara perihal penggandaan fisik. “Kualitas” produksi yang baik dan juga distribusi rilisan fisik di atas kertas memerlukan biaya yang tidak sedikit.
2. Dilema antara Underground dan Komersialisasi
Sejak dulu, skena musik metal di Indonesia punya filosofi kuat soal independensi. Namun di sisi lain, kebutuhan untuk bertahan hidup dan untuk lebih berkembang dari sisi fan-base, menuntut mereka membuka diri terhadap sponsor, label, atau bahkan konten komersial.
Dengan label sebagai musik "underground", banyak band Metal yang terjebak dalam dilema yakni apakah bakal terus menjajaki jalan indie yang mengutamakan kemandirian, atau justru bersedia disponsori merek tertentu, hingga ikut festival besar.
Sebagian komunitas masih menganggap jika mereka masuk ke arus utama atau "mainstream", hal itu merupakan bentuk “pengkhianatan” terhadap semangat underground. Tapi di era pasca-pandemi, banyak band justru melihatnya sebagai peluang untuk bisa tetap berkarya dan menjangkau lebih banyak pendengar tanpa kehilangan jati diri.
Menurut penulis sendiri, komersialisasi dari sisi penyebaran karya musik bukanlah hal yang tabu – bahkan keharusan yang perlu dijaga adalah orisinalitas ide bermusik dan karya musiknya sendiri.
Agaknya bakal percuma punya karya yang secara musikalitas, skill maupun teknis tapi tidak sulit menjangkau telinga khalayak luas. Tanpa pendengar, seorang musisi jelas bakal kesulitan untuk menjadikan karyanya punya manfaat ekonomi.
3. Minimnya Dukungan Infrastruktur dan Venue
Nah ini yang paling menjengkelkan menurut penulis. Venue gig metal di Indonesia cenderung berputar di tempat yang sama. Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Malang, dan Denpasar masih jadi poros utama.
Belakangan kota-kota di Pantura mulai unjuk gigi. Namun di banyak daerah lain, band-band metal harus berjuang keras mencari tempat tampil yang aman dan layak. Di beberapa kota kecil, stigma terhadap metal masih kuat, dianggap “keras”, “barbar”, bahkan “satanik”. Hal ini membuat banyak gig batal karena tekanan dari masyarakat atau pihak berwenang.
Akibatnya, perkembangan scene metal di daerah menjadi stagnan. Padahal menurut penulis, lebih “serem” ngepam acara genre musik sebelah – yang katanya merupakan warisan budaya lokal (kalian tebak lah yang mana) daripada ngepam acara konser musik Metal. Kadang yang lebih sulit bukan bikin lagu, tapi cari tempat buat manggung tanpa dibubarkan.
Pihak keamanan mungkin harus sedikit membuka diri untuk mengenal soal skena musik ini, agar tak buru-buru membubarkan konser yang sejatinya tak berbeda dengan acara musik lain.
4. Persaingan di Era Digital dan Algoritma
Sekarang semua band bisa rilis lagu secara online, tapi justru di situlah tantangan baru muncul: algoritma platform streaming lebih menguntungkan musik mainstream yang gampang diterima khalayak luas.
Bahkan, belakangan, berkat berkembangan teknologi, banyak musisi atau setidaknya karya ciptaan mereka, yang justru mendapat popularitas dari media sosial.
Ya, media sosial kini memegang peran dalam distribusi musik ke telinga masyarakat lewat fitur menambahkan lagu pada unggahan pengguna. Menariknya, setidaknya merujuk pengalaman penulis, musik-musik yang "menembus" algoritma kebanyakan bergenre pop. Musik metal tak punya ruang untuk "mejeng" jadi sound populer di TikTok maupun Instagram.
Metal. dengan durasi panjang, vokal growl, dan struktur kompleks lebih sering kalah dalam chart Spotify dan platform musik lain. Akibatnya, meski punya basis penggemar solid, eksposur digital mereka tetap terbatas.
Band-band metal kini dituntut untuk paham digital marketing, branding, dan konten visual, sesuatu yang dulu tidak menjadi fokus utama scene metal. Ada yang berhasil menembus audiens baru lewat YouTube, tapi banyak juga yang masih terjebak di lingkar komunitasnya sendiri.
5. Regenerasi dan Tantangan Komunitas
Generasi muda metalheads mulai bergeser ke arah metalcore atau post-hardcore, sementara penggemar klasik lebih loyal pada death metal dan thrash.
Perbedaan selera ini kadang memunculkan jarak antar komunitas. Kadang bahkan menjadi “persaingan” genre yang menurut penulis justru kontraproduktif untuk perkembangan skena Metal itu sendiri.
Kenapa sulit sekali mencairkan persaingan antar genre ini? Apakah konser musik Metal harus melulu isinya genre music tertentu saja? Gak bisakah dalam satu event Metal kita bikin model campursari – ada Black Metal, DeathMetal, Hardcore, EMO, apalah gitu? Eh EMO masuk Metal nggak ya?
Selain itu, regenerasi di level organisasi juga jadi masalah. Banyak komunitas metal lokal bergantung pada beberapa figur lama, ketika mereka vakum, scene bisa langsung mati suri.
Beberapa kota sudah mencoba mengatasinya lewat festival komunitas atau kolaborasi antar scene lintas kota seperti Rockin Solo dan Ubernoize yang mengagendakan event “Road to…” tapi konsistensi masih jadi kunci.
6. Pandangan Sosial dan Stigma yang Belum Hilang
Meskipun metal sudah jauh lebih diterima dibanding dulu, stigma negatif masih sering muncul di masyarakat.
Penampilan ekstrem, lirik gelap, dan simbol-simbol visual sering disalahartikan. Padahal banyak band metal yang justru mengangkat isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Contoh paling mudah adalah Voice of Baceprot. Band metal asal Garut yang semua personilnya diisi perempuan berhijab ini, membuktikan bahwa skena Metal "aman" untuk semua kalangan, termasuk perempuan.
Selain itu, banyak konser Metal yang menerapkan aturan ketat untuk menghormati ibadah. Saat adzan berkumandang, acara break sementara. Masih butuh waktu dan edukasi publik agar metal dipahami bukan sebagai “kekerasan”, tapi ekspresi artistik dan intelektual yang kompleks.
7. Harapan dan Arah ke Depan
Meski penuh tantangan, optimisme tetap ada. Banyak Band-band Metal Tanah Air menunjukkan bahwa metal Indonesia bisa bersuara keras, bahkan di panggung dunia. Band-Band lokal juga sudah mulai melakukan tur keluar negeri, entah event tunggal atau merupakan bagian dari tur band lain yang lebih besar. Tentunya dukungan komunitas / skena Metal dan para sponsor sangat diperlukan.
Tren eksperimental, menggabungkan unsur lokal, lirik berbahasa daerah, atau kolaborasi lintas genre mulai menciptakan identitas baru bagi metal Indonesia. Dan, di balik itu semua, komunitas masih jadi jantung utama: solidaritas, gigs kecil, merch mandiri, dan semangat do it yourself yang tak pernah mati.
Skena Metal di Indonesia sedang berada di persimpangan, antara idealisme dan realita, antara underground dan mainstream, antara digitalisasi dan akar komunitas.
Namun satu hal tetap jelas, selama masih ada semangat, riff berat, dan crowd yang berteriak di moshpit serta membeli rilisan fisik maupun merchandise, skena METAL Indonesia akan terus hidup.
Address
JDC 6th floor - Business Centre
Jl. Gatot Subroto No. 53 Jakarta 10260
A Metal Project Official Website
© 2025
CONTACT US
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER